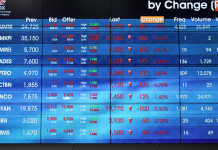(Vibiznews-Kolom) Tahun 2045 menjadi semacam titik kulminasi bagi Indonesia. Dalam berbagai dokumen kebijakan dan skenario pembangunan, angka tersebut berdiri seperti mercusuar – menjadi negara berpenghasilan tinggi. Namun bagaimana cara mencapainya bukanlah pertanyaan teknis semata, melainkan transformasi besar dalam lanskap bisnis nasional.
Salah satu tantangan utama adalah dominasi perusahaan mikro di ekonomi Indonesia. Berdasarkan sensus ekonomi 2016, lebih dari 97 persen perusahaan di Indonesia tergolong mikro, dan hampir 60 persen tenaga kerja berada di dalamnya—banyak di antaranya bersifat informal. Perusahaan-perusahaan ini memang memberikan penghidupan, tetapi kontribusinya terhadap produktivitas dan akumulasi modal sangat terbatas.
McKinsey Global Institute dalam laporannya menggarisbawahi bahwa negara-negara yang berhasil naik kelas—seperti Korea Selatan, Polandia, dan Meksiko—selalu menunjukkan pola yang sama: pergeseran struktur usaha ke arah perusahaan menengah dan besar. Perusahaan dengan lebih dari 250 karyawan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, memiliki modal kerja lebih tinggi, dan cenderung menjadi pusat inovasi, pelatihan, dan integrasi rantai pasok.
Untuk Indonesia, skenario yang ditawarkan cukup ambisius: jumlah perusahaan menengah dan besar perlu dilipatgandakan hingga tiga kali lipat—menjadi 200.000 dan 40.000 unit. Tujuannya bukan hanya sekadar memperbanyak, tetapi juga untuk mengalihkan tenaga kerja dari sektor informal ke dalam perusahaan produktif dengan upah lebih tinggi. Dalam simulasi 2045, proporsi pekerja di perusahaan besar akan meningkat dari 15 persen menjadi 31 persen.
Dalam proses ini, modal per pekerja—yang menjadi kunci produktivitas—ditargetkan naik dari US$31.000 menjadi US$100.000. Ini hanya mungkin jika perusahaan-perusahaan tersebut meningkatkan investasi mereka dalam alat kerja, pelatihan, teknologi, dan infrastruktur. Sebagai contoh, perusahaan besar dapat mendorong penggunaan AI dalam rantai logistik, sementara perusahaan menengah dapat memodernisasi proses manufaktur melalui digitalisasi ringan.
Tentu saja, tidak semua sektor memiliki jalur yang sama. Laporan tersebut mencatat bahwa sektor jasa akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan, hingga 70 persen PDB. Ini termasuk layanan profesional, teknologi informasi, perbankan, logistik, dan sektor pariwisata berkelanjutan. Namun tantangannya jelas: sektor jasa di Indonesia saat ini memiliki produktivitas rendah dan didominasi oleh usaha informal. Maka transformasi sektor ini butuh modernisasi, formalisasi, dan penguatan talenta digital.
Di sisi lain, sektor manufaktur yang sempat meredup memiliki potensi untuk bangkit kembali. Nilai tambah manufaktur turun dari 32 persen pada 2002 menjadi hanya 19 persen pada 2023. Untuk mengubah arah, Indonesia perlu mendorong kompleksitas ekonomi, bukan hanya mengekspor bahan mentah seperti batu bara atau sawit, melainkan masuk ke produk olahan: bioplastik, baterai kendaraan listrik, dan paduan logam lanjutan. Apalagi Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
Skenario juga mencakup potensi dalam rantai pasok global. Saat negara-negara dunia merestrukturisasi rantai suplai karena geopolitik dan pandemi, Indonesia dapat menawarkan diri sebagai alternatif lokasi produksi—terutama untuk elektronik, tekstil, dan kendaraan. Tapi untuk itu, Indonesia perlu mempercepat konektivitas pelabuhan, reformasi logistik, dan penyediaan tenaga kerja terampil.
Transformasi produktivitas tidak hanya soal perusahaan besar, tetapi juga petani kecil dan pengusaha mikro. Di sektor pertanian, tantangan terbesar adalah ukuran lahan yang kecil (rata-rata hanya 0,6 hektar), rendahnya penggunaan benih unggul, dan minimnya adopsi teknologi digital. Hanya sekitar 2 persen petani menggunakan platform e-commerce, dan sebagian besar belum mengenal drone atau sistem irigasi otomatis.
Sementara itu, urbanisasi menjadi faktor krusial lainnya. Sekitar 70 juta orang diprediksi akan pindah ke kota hingga 2045. Jika tidak dikelola dengan baik, mereka akan terjebak di pekerjaan informal di sektor jasa berproduktivitas rendah. Sebaliknya, dengan perencanaan cerdas seperti konsep kota 15 menit, mereka bisa menjadi tenaga kerja yang produktif. Di sinilah pentingnya investasi dalam infrastruktur perkotaan dan akses pendidikan vokasi.
Untuk mendorong transformasi ini, laporan menekankan pentingnya lima bentuk modal: modal keuangan, manusia, institusional, infrastruktur, dan kewirausahaan. Di semua lini, Indonesia masih tertinggal. Misalnya, rasio aset pensiun hanya 2 persen dari PDB, dibandingkan 76 persen di negara maju. Indeks keterampilan tenaga kerja rendah, dan waktu rata-rata untuk membuka bisnis masih 43 hari, dengan biaya lebih dari US$1.300. Padahal di beberapa negara maju, hanya butuh waktu tiga hari dan biaya di bawah US$100.
Terakhir, jumlah perusahaan formal baru di Indonesia masih rendah: hanya 0,3 per 1.000 penduduk usia kerja per tahun. Ini jauh di bawah Brasil (5,1) dan banyak negara ASEAN. Oleh karena itu, upaya membangun ekosistem kewirausahaan butuh lebih dari sekadar pelatihan. Dibutuhkan akses pendanaan awal, inkubator yang berfungsi baik, dan kolaborasi dengan perusahaan besar.
Laporan ini menyimpulkan bahwa Indonesia tidak kekurangan cita-cita, tetapi perlu mempercepat langkah agar tidak terjebak dalam “jebakan negara menengah”. Jalan menuju 2045 menuntut perubahan menyeluruh—dari cara perusahaan dibentuk, tumbuh, hingga mengelola pekerjanya. Jika berhasil, Indonesia bisa mewujudkan bukan hanya archipelago economy, melainkan benar-benar menjadi enterprising archipelago yang produktif, adil, dan tangguh menghadapi masa depan.
Dalam proses ini, kisah-kisah nyata menjadi penting untuk mengisi ruang statistik. Ambil contoh sebuah perusahaan manufaktur menengah di Semarang yang memulai transformasi pada 2027. Dulu mereka hanya membuat onderdil untuk motor lokal. Namun setelah bergabung dalam program kemitraan industri nasional, mereka mulai memproduksi komponen EV untuk pasar ASEAN. Mereka memanfaatkan insentif pajak, pembiayaan dari lembaga penjaminan modal, dan mengikuti pelatihan otomasi industri. Lima tahun kemudian, tenaga kerja mereka naik dari 48 ke 200 orang, dan ekspor menjadi 60 persen dari pendapatan.
Cerita lain datang dari sektor pariwisata berbasis komunitas. Di Labuan Bajo, koperasi lokal membangun ekowisata laut bekerja sama dengan perusahaan teknologi dari Bandung yang menyediakan sistem pemesanan daring, pelatihan hospitality, dan pendampingan sertifikasi CHSE. Hasilnya, dalam waktu empat tahun, pendapatan komunitas naik tiga kali lipat, dengan efek ganda ke UMKM makanan, kerajinan, dan transportasi lokal. Kolaborasi seperti ini menjadi contoh konkret bagaimana perusahaan kecil dapat tumbuh jika dikelilingi ekosistem yang sehat.
Transformasi besar seperti ini tidak bisa ditinggalkan pada satu sektor saja. Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus membangun kesepahaman bahwa pertumbuhan tidak boleh meninggalkan produktivitas. Setiap regulasi, proyek, atau kemitraan harus ditimbang dari seberapa besar ia menggerakkan produktivitas nasional.
Karena itu, tantangan ke depan bukan hanya memperbanyak perusahaan besar, tapi memastikan bahwa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dapat “naik kelas” secara berkelanjutan. Tanpa itu, ekonomi Indonesia hanya akan bertumpu pada sedikit pemain besar dan tetap rapuh di tengah guncangan global.
Namun jika transformasi ini dijalankan serius, maka bukan tidak mungkin pada 2045, Indonesia bukan hanya negara besar dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah, tetapi juga dari daya saing perusahaan-perusahaannya. Dan saat itu tiba, barulah benar Indonesia layak disebut sebagai the enterprising archipelago.